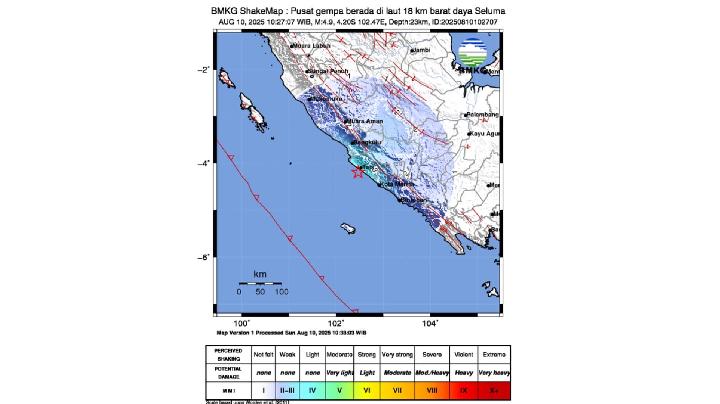TEMPO.CO, Jakarta - Setiap hari, Ibrahim Abu Naji terbangun di atas alas tidur dari lembaran kardus tipis di dalam sebuah ruang kelas yang penuh sesak, yang dialihfungsikan menjadi tempat penampungan, di Kota Gaza.
Badannya terasa sakit karena lantai yang keras, dan tubuhnya yang ringkih berjuang untuk merawat sembilan anak dan cucu yang tidur berimpit di dekatnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di luar, langit-langit bergetar setiap kali ada serangan udara Israel. Pria Palestina berusia 65 tahun itu menatap ruangan yang temaram sambil bertanya dalam hati, "Akankah kami selamat hari ini?"
Terpaksa meninggalkan rumahnya beberapa kali, Ibrahim mengungsi dari permukiman Shuja'iyya di Gaza tengah, kemudian menuju Rafah, dan akhirnya tiba di Kota Gaza.
"Penderitaan ini tidak seperti yang pernah saya alami, bahkan dalam perang-perang sebelumnya," kata Ibrahim kepada Xinhua seperti dilansir Antara pada Jumat.
"Tidak ada lagi tempat yang aman. Setiap kali kami menemukan sedikit kedamaian, perintah evakuasi datang. Kami meninggalkan hampir segalanya, seperti daun yang tersapu angin."
Ibrahim berhenti sejenak, suaranya terdengar berat akibat kelelahan. "Saya sudah tua. Saya tidak bisa berjalan jauh. Punggung saya sakit karena tidur di lantai. Tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan, dan tidak ada sanitasi yang layak. Ini bukan kehidupan. Ini adalah kematian yang perlahan," ujarnya.
Saat serangan Israel di Gaza memasuki bulan ke-19, warga lanjut usia (lansia) Palestina menghadapi kelaparan yang kian parah, pengungsian berulang kali, kurangnya perawatan medis, dan ancaman tanpa henti terhadap keselamatan mereka dalam apa yang disebut sebagai krisis kemanusiaan terbesar dalam hidup mereka.
Di rumahnya yang rusak di Kota Deir al-Balah, Jalur Gaza tengah, Dalal al-Naji (84) duduk terbungkus selimut tipis yang nyaris tak dapat melindunginya dari hawa dingin. Suara wanita Palestina itu bergetar saat menggambarkan migrasi paksa yang belum lama ini dialaminya.
"Kami sudah tua. Kami tidak bisa lari saat bom jatuh. Kami tidak bisa berdiri berjam-jam dalam antrean makanan," tutur Dalal.
"Sebuah roket jatuh hanya beberapa meter dari rumah kami baru-baru ini. Saya pikir jantung saya akan berhenti. Saya tidak bisa bangun sampai anak laki-laki saya menggendong saya," ujarnya.
"Yang saya inginkan sekarang adalah satu malam yang damai, tidak ada pesawat menderu di udara, tidak ada rasa takut bahwa langit-langit akan runtuh. Saya ingin mati dengan tenang," ia menambahkan, dengan mata berkaca-kaca.
Pengungsi wanita lainnya, Naima al-Naji (72), mengisahkan perjuangannya untuk mendapatkan makanan dan obat-obatan.
"Kami menunggu berjam-jam demi sekantong kecil roti dan sekaleng kacang," ujarnya kepada Xinhua. "Kadang-kadang saya tidak mendapatkan apa-apa. Tekanan darah saya tinggi, tetapi saya tidak bisa menemukan obat. Saya berbaring dan membaca Al-Quran untuk menghabiskan waktu."
Naima mengenang masa-masa yang lebih sederhana. "Kehidupan kami sederhana. Kami hidup dengan roti dan tomat, dan kami bahagia. Sekarang, kami tinggal di tenda-tenda yang dikelilingi reruntuhan dan kematian. Di manakah dunia? Apakah tidak ada yang melihat ini?
"Saya lebih mengkhawatirkan anak-anak daripada diri sendiri. Kami sudah tua, sudah mendekati akhir perjalanan hidup kami. Mereka baru saja memulai kehidupan, tetapi jalannya gelap," ujarnya sambil menggenggam tangan cucu perempuannya.
Mohammed al-Majayda (75), warga Kota Khan Younis di Gaza selatan, mengenang pengungsian pertamanya saat perang 1967.
"Saat itu, para tetangga membuka rumah mereka untuk kami. Kini, semua orang menderita, dan tidak ada yang dapat membantu," tuturnya.
Sejak Oktober 2023, Mohammed telah mengungsi lebih dari 10 kali. "Ada masa di saat makanan tidak ada selama dua hari," katanya. "Saya sudah tua dan lemah. Tidak ada obat, tidak ada dokter, tidak ada ambulans."
"Saya merasa ini adalah akhir dari kehidupan. Tidak ada yang bertanya tentang kami, baik pemerintah maupun institusi. Kami dilupakan," ujarnya dengan suara pecah menahan tangis.
Ketiadaan obat-obatan, pemadaman listrik, dan kurangnya air bersih memperburuk kondisi pasien lansia. Banyak yang telah kehilangan keluarga atau tinggal jauh dari sanak saudara akibat pengungsian atau penangkapan.
Mohammed Abu Jamea, seorang sukarelawan amal dari Kota Gaza, mengatakan, "Setiap hari, banyak lansia yang datang, kelelahan karena kelaparan dan fatig. Banyak dari mereka yang pingsan karena tekanan psikologis dan pengabaian. Kami mencoba menawarkan makanan dan selimut, tetapi sumber daya kami terbatas, dan permintaannya sangat besar."
"Mereka tidak meminta istana atau uang. Mereka ingin hidup dengan martabat. Mereka menginginkan rumah, obat-obatan untuk meringankan rasa sakit, dan kedamaian sehingga mereka tidak dibom saat sedang tidur," kata Abu Jamea.
"Ketika mendekati akhir hidup, mereka berharap untuk bisa beristirahat," imbuh Abu Jamea. "Sebaliknya, mereka menghadapi awal dari bencana baru. Namun, kami tidak akan meninggalkan tanah kami. Kami akan mati di sini, sebagaimana mereka hidup, meskipun beralaskan tanah."